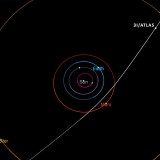TIMES TEMANGGUNG, JEMBER – Pernahkah kalian menonton sebuah film atau iklan yang menempatkan aktor perempuan hanya sebagai ikonik dari sebuah cerita saja? Aktor perempuan itu tidak memiliki pengaruh pada plot cerita, serta perkembangan karakter yang minim. Mereka hanya sebatas sebagai objek yang dilihat.
Hal ini dibahas oleh Laura Mulvey (seorang ahli teori film feminis dari Inggris) pada tahun 1975 dalam esainya yang berjudul Visual Pleasure and Narrative Cinema yang diterbitkan dalam Majalah film Screen. Laura mengatakan femonema yang tersebut diatas sebagai “The Male Gaze” dengan menjabarkan bagaimana film-film Hollywood menggunakan perempuan sebagai pengalaman visual belaka untuk memenuhi fantasi laki-laki.
Pada teori feminism, the male gaze (pandangan laki-laki) merupakan sebuah tindakan yang menggambarkan perempuan dalam seni rupa dan literatur melalui pers yang maskulin dan heteroseksual dengan menggambarkan perempuan sebagai objek seksual untuk menyenangkan pemirsa laki-laki. Pada film, the male gaze biasanya diterapkan dalam pengambilan gambar yaitu dengan menggunakan perspektif penonton pria.
Lebih lanjut, the male gaze biasanya membuat perempuan ditampilkan dalam dua level erotisme, yakni sebagai objek erotik bagi aktor didalam film ataupun objek erotik bagi penonton pria. Alur yang ditampilkan dengan menggambarkan perempuan sebagai objek yang dilihat laki-laki melalui kamera movement yang kemudian di-forward untuk penonton.
Visualisasi yang demikian menciptakan peran laki-laki yang lebih dominan dengan menampilkan perempuan sebagai objek yang pasif. Sehingga, the male gaze memiliki dua komponen utama, yaitu: perempuan yang menjadi objek tatapan laki-laki, serta penonton yang akhirnya dituntut supaya bisa relate (menyesuaikan diri) dengan karakter laki-laki.
Contoh khas penerapan the male gaze dalam film antaranya: bidikan close-up perempuan yang mengikuti arah gerak mata laki-laki dalam mengeksplor tubuh perempuan, bidikan bergerak dan akhirnya terpaku pada tubuh perempuan, dan sebagainya.
Adapun teory of gaze (pandangan), pertama kali diperkenalkan oleh filsuf eksistensialis, Jean-Paul Sartre dalam concept of le regard. Sartre menjelaskan bahwa tindakan menatap pada seseorang dapat menciptakan perbedaan terhadap tenaga subjektif yang dirasakan oleh penatap ataupun yang ditatap. Hal ini disebabkan karena yang ditatap dianggap sebagai objek (benda), bukan manusia.
Pada akhirnya, ditatanan dunia yang tidak seimbang ini (interm of gender) kenikmatan dalam menatap atau melihat terarah menjadi dua, yaitu: Aktif (laki-laki) dan sebalikanya perempuan sebagai objek pasifnya. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan the male gaze. Dimana tubuh perempuan dijadikan sebagai objek yang memberikan kenikmatan melalui voyeurism (melihat atau menatap untuk memuaskan hasrat seksual) dan skopofilia (mendapatkan kesenangan dengan melihat).
Konsep ini (the male gaze) pada akhirnya meluas dari film ke berbagai media apapun. Perempuan digambarkan sebagai pengalaman yang menarik dalam dunia nyata. Tubuh perempuan digunakan untuk menjual dan menarik perhatian (utamanya pria cis heteroseksual). Misalnya: perempuanlah yang lebih sering ditampilkan dalam iklan, sampul majalah, serta media sosial lainnya.
Tidak hanya itu, biasanya selebriti perempuan berpose provokatif di sampul majalah, berpakaian minim, dan adanya penyanyi perempuan yang cenderung tampil memamerkan banyak kulit, dll. Selain itu, dalam dunia literasi juga masih banyak penulis laki-laki yang menggambarkan perempuan hanya sebagai objek didalam bukunya dan kebanyakan sebagai objek seksual. Penulis yang cukup terkenal dalam hal ini adalah Haruki Murakami dimana ia selalu terobsesi dengan perempuan, namun bukan sebagai manusia yang utuh melainkan objek seksual belaka.
Tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa media-media yang sering kita konsumsi begitu sarat akan male gaze?
Untuk menjawab hal tersebut, Laura Mulvey mengemukakan bahwa ketidaksetaraan gender dalam hal ini perbedaan kekuatan sosial dan politik antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kekuatan sosial yang pada akhirnya dapat mengendalikan representasi gender dalam film. Selain itu, the male gaze (pandangan laki-laki) telah menjadi sebuah konstruksi sosial yang diturunkan dari industri patriarki. Pasalnya, industri perfilman, industri kreatif hakikatnya dibuat oleh laki-laki dan untuk laki-laki sebagai sarana untuk memenuhi fantasinya akan gambaran ideal seorang perempuan.
Dalam dunia perfilman, kebanyakan laki-laki yang menjadi penulis film, laki-laki yang membuat film, dan ditargetkan kepada laki-laki pula. Oleh karenanya, kebanyakan film biasanya menjadikan laki-laki sebagai peran utama dalam cerita sedangkan perempuan hanya sebagai karakter yang diberikan fungsi terbatas untuk melayani atau mencapai tujuan protagonis si laki-laki.
Kendati konsep the male gaze dikemukakan oleh Laura Mulvey pada tahun 1970-an yang disesuaikan pada konteks situasi dan kondisi pada waktu itu. Kenyataannya, the male gaze-pun masih bisa dijumpai pada film-film modern masa kini. Contohnya: pada film Transformers (2017) karya Michael Bay, dimana pemeran perempuan dieksplorasi secara seksual dengan berbagai cara padahal tidak memiliki relevansi dengan alur ceritanya. Selain itu yang begitu akrab dengan kita berbagai cinema dalam Disney Princess dimana putri-putri Disney hanya akan bahagia ketika bertemu dengan laki-laki.
Hal itu seolah mengemukakan bahwa perempuan tidak bisa bahagia hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Tidak hanya di film Hollywood, pada film lokal Indonesia pun dapat banyak dijumpai the male gaze yang begitu sarat terjadi.
Pertanyaan terbesar selanjutnya, mengapa the male gaze menjadi masalah besar padahal sebatas terjadi pada media dan bukan pada dunia nyata?
Menjadi rahasia umum bahwa media itu begitu dekat dengan kita, dengan kehidupan sehari-hari kita, dan kita mengonsumsinya dalam keseharian tanpa henti. Semua yang kita cerna lama-kelamaan akan menjadi hal lumrah yang diinternalisasi dan diamini. Sehingga, cara berfikir (mindseat), cara bertindak (tingkah laku) pada kehidupan nyata dipengaruhi dan mengikuti segala hal yang dikonsumsi atau diliat dari media. Media pada akhirnya mengarahkan pada informasi harapan, budaya, dan identitas pribadi seseorang.
Adanya the male gaze yang mengobjektifkasi perempuan dalam media akhirnya membuat objektifikasi perempuan pada dunia nyata. Dampak dari the male gaze telah diinternalisasi sampai batas tertentu oleh laki-laki dan perempuan, dan mungkin kita bahkan tidak menyadarinya. Selain itu, the male gaze memberikan pengaruh yang signifikan pada cara pandang seseorang terhadap bagaimana laki-laki memandang perempuan, bagaimana perempuan memandang dirinya dan bagaimana perempuan memandang perempuan lainnya.
Pertama, laki-laki mereduksi perempuan sebagai makhluk (objek) yang pasif. Sehingga hal ini menjadi salah satu usaha patriarki untuk menjaga status-quo laki-laki sebagai pengendali seksual. Tidak hanya itu, apabila seorang perempuan mendapatkan perlakuan buruk dari laki-laki hal itu dilumrahkan dengan alasan bahwa “perempuan memang begitu takdirnya sebagai objek”.
Selanjutnya, perempuan mengobjektifikasi dirinya sendiri dan mengakui bahwa perempuan hanyalah sebagai objek yang dipandang dan laki-laki yang memandang. Sehingga, secara alami pengaruh male gaze meresap kedalam persepsi dan harga diri perempuan yang kemudian menghadirkan tekanan untuk dapat menyesuaikan diri dengan pandangan patriarki ini. Hal inipun membentuk cara pikir perempuan tentang tubuh, kemampuan dan tempat untuk diri mereka didunia serta dihadapan perempuan yang lain.
Tidak jarang dijumpai perempuan yang memuji sesamanya atas kecantikan atau perawakan yang dimiliki. Implikasinya, perempuan mudah insecure dan melakukan berbagai hal untuk memenuhi standardisasi cantik yang dibuat oleh media terlebih dengan adanya the male gaze. Perempuan berlomba-lomba berpenampilan se-baik mungkin untuk menarik perhatian laki-laki. Sehingga tidak jarang perempuan menjadi sasaran empuk kapitalisme berkedok produk kecantikan, style berpakaian, dll.
Secara sederhana, the male gaze telah berhasil membawa perempuan yang semula adalah makhluk yang utuh berafiliasi menjadi objek semata yang direduksi melalui tatapan. Sehingga pada intinya, the male gaze telah berhasil menghambat pemberdayaan perempuan dan advokasi diri perempuan dengan mendorong objektifikasi dirinya dalam penghormatan kepada laki-laki serta patriarki pada umumnya.
Untuk memutus mata rantai the male gaze, tentu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan berbagai langkah supaya tidak lagi melanggengkannya diberbagai media. Dibalik itu, kita bisa mencoba memutus mata rantai male gaze dimulai dari yang sederhana yaitu diri kita sendiri.
Laki-laki sudah sepatutnya memandang perempuan sebagai manusia yang utuh dan teman sosial yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dengannya. Sedangkan perempuan harus bisa memvalidasi dirinya sendiri, menghargai dirinya, dan menentukan nilai dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, perempuan mampu meningkatkan elektabilitasnya melalui berbagai hal sehingga ia tidak hanya dipandang sebatas kecantikan yang ia miliki. Sebagai contoh, memperkaya khazanah keilmuwan dengan aktif membaca buku untuk muatan intelektual, memperkuat mentalitas diri melalui berbagai pelatihan dan seminar, menghasilkan berbagai karya pun aktif diberbagai kegiatan sosial sebagai bentuk aktualitas diri, dan sebagainya.
Pada akhirnya, dengan kegigihan perempuan atas kesadaran diri sebagai manusia yang utuh (tidak lagi terkungkung oleh standarisasi cantik semata) perempuan mampu membuktikan diri pada mata dunia bahwa ia adalah makhluk Tuhan yang luar biasa dan begitu berharga.
***
*) Oleh: Isna Asaroh, Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Jember.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: The Male Gaze: Objektifikasi Perempuan yang Menghambat Pemberdayaan Diri
| Pewarta | : |
| Editor | : Faizal R Arief |